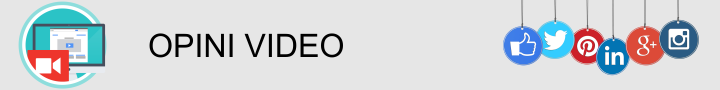Oleh: Anga Eko Ardianto

Aku terdiam mendengar keputusan majelis partai yang dipimpin bapakku. Keringat dingin mengucur deras di leherku. Aku tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun.
Mulutku serasa terkunci setelah majelis memutuskan bahwa aku yang diusulkan maju menjadi calon bupati dalam waktu yang begitu cepat tanpa meminta persetujuan dariku.
Politik memang kejam, tidak seperti di perusahaan. Setidaknya begitulah yang sering dikatakan bapak kepadaku. Kalau di perusahaan, kita dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi karena prestasi yang kita miliki.
Tidak seperti politik, siapa saja boleh berpartisipasi di dalamnya, Tanpa perlu memandang prestasi yang telah dicapai.
“Kau harus siap, nak. Termasuk siap untuk menerima kekalahan”, seru bapakku waktu itu. Aku tidak dapat menolak perintah dari bapakku. Karena aku tahu kalau menolaknya, sama saja aku tidak membahagiakannya.
Tetapi, aku masih hijau. Minim pengetahuan akan politik. Yang aku tahu, politik tidak memandang keturunan siapa, dari mana asalnya, dan berapa kekayaannya. Yang dipandang adalah kemampuan untuk bersaing memperebutkan simpati rakyat agar dipilih, tak peduli bagaimanapun caranya.
“Bagaimana cara agar masyarakat memilihku?. Cara apa yang harus kugunakan untuk meyakinkan mereka bahwa aku mampu memimpin orang yang memiliki latar belakang bermacam-macam?”.
Istriku tidak habis pikir dengan keputusanku yang menanggalkan jabatan strategis di perusahaan negara demi maju dalam pilkada. Dia menganggap aku hanya menjadi korban politik bapakku dan keputusan untuk mundur dari perusahaan negara adalah suatu bencana yang besar.
Sepertinya, kita tinggal menunggu sebuah kehancuran yang akan datang menerpa keluarga kecil kita.
“Kenapa harus kamu yang maju, kok bukan Seno saja?”, tanya istriku. Diam. Itulah yang dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan istriku. Tidak ada kata lain yang dapat diucapkan pada istriku.
Ini adalah mandat dari bapak, selaku pemimpin partai. Bapak mengira, sudah saatnya aku terjun ke dunia politik, meninggalkan jabatan direktur di perusahaan milik negara yang mengangkat namaku menjadi setinggi ini.
Aku harus siap apapun hasilnya. Ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Panggung politik adalah perjalanan hidup yang baru, setelah lengser dari dunia perusahaan.
Dan Seno, adikku merupakan pengurus partai yang dipimpin bapak. Dia lebih mengerti tentang politik. Dia masih sangat muda. Terpaut 5 tahun dari usiaku saat ini yang menginjak 35 tahun.
Pembawaannya yang ramah, mudah bergaul, dan pantang menyerah sangat cocok untuk dijadikan calon. Apalagi dia bisa berbaur dengan kaum akar rumput, yang memiliki mayoritas suara di daerah ini.
Awalnya, aku mengira bahwa bapak yang akan memilihnya. Namun perkiraanku meleset. Bapak menganggap bahwa akulah yang pantas dicalonkan. Bukan Seno.
Berhari-hari aku memikirkan hal itu. Namun tidak ada solusi yang terbaik untuk membatalkan pilihan bapak. Semua suara bulat mendeklarasikanku menjadi calon bupati dengan didampingi senior partai pengusung lain.
Apa yang harus kulakukan untuk meyakinkan rakyat bahwa aku bisa memimpin mereka?.Keriuhan kampanye tidak menghntikan kekhawatiranku yang menduga akan kalah di pilkada. Bahkan kalah telak.
Semua simpatisan bergembira menyambutku. Namun ada juga yang membayangkan kekalahanku. Memang, ini adalah penampilan pertamaku di panggung politik.
“Berani juga mereka mencalonkan putra mahkota ketua umum sebagai bupati” “Apa mereka tidak takut kalah?. Kan anaknya belum paham betul tentang dunia politik” “Mungkin ini adalah siasat mereka untuk memenangkan pilkada. Mengenalkan putranya ke panggung politik”.
Aku kenal dengan lawan politikku. Mereka kenyang pengalaman karena merintis karir politik dari bawah. Teknik menghadapi masyarakat sudah mereka kuasai. Program kerjanya tak perlu dipertanyakan lagi.
Semua tersusun secara rapi dan terencana dengan baik. Tidak seperti aku yang langsung dicalonkan tanpa melalui proses kaderisasi terlebih dulu. Tanpa tahu karakter rakyat yang akan kupimpin jika terpilih.
Semua terjadi secara tiba-tiba. Tanpa melalui proses panjang nan berliku. Harus siap kapanpun dibutuhkan. Dan tanpa pikir panjang terlebih dulu.
Istriku tak henti-hentinya mengomel. Menganggap aku terlalu nurut omongan bapak. Memang harusnya seperti itu, seorang anak harus menuruti perintah orangtuanya asalkan tidak disuruh untuk melakukan hal negatif.
“Jangan terlalu lembut sama bapak. Tolak keinginan bapak dengan baik-baik. Sayang jabatan jadi direktur yang kau rintis dari bawah terbuang sia-sia demi mengikuti pilkada yang hasilnya tidak pasti”.
“Sudahlah.Turuti saja keinginan bapak. Mungkin ini yang terbaik. Bapak menyiapkan aku menjadi kader partai untuk jangkapanjang”, kataku mencoba menenangkan istriku.
“Tapi, mas…”Aku menempelkan telunjukku ke bibir. Istriku tidak melanjutkan pembicaraan. Dia masuk ke dalam kamar sambil mengeluarkan air mata. Mungkin dia takut tidak dapat hidup mewah lagi seperti dulu.
Tidak bisa melihatku menggunakan jas dan dasi seperti ketika menjadi direktur perusahaan milik negara. Langkah kakiku mengikuti istriku ke dalam kamar. Kami beristirahat. Tak lama kemudian mataku tertutup. Aku terlelap.
Lawan politikku berkampanye dengan begitu lihainya. Mereka mampu menarik simpati warga dengan sangat baik. Tidak kusangka, sang petahana ini masih mampu memikat hati rakyat walaupun tersandung kasus.
Dia tidak terpengaruh dengan kasus yang membelitnya. Bahkan dia semakin gencar berkampanye dan berkoar bahwa dia tidak terlibat dalam kasus itu.Simpatisanku juga tidak kalah semangat.
Mereka mendukung pencalonan diriku meski hanya segelintir. Tidak sebanyak simpatisan lawan yang sudah merasakan tangan dingin sang petahana yang telah memimpin kabupaten dengan caranya yang menawan.
“Waduh, bagaimana ini, simpatisan kita hanya segelintir. Masih kalah dengan simpatisan lawan”.“Biarlah. Kita usaha saja semampu kita. Toh, ini penampilan perdanaku di panggung politik. Aku hanya mampu melakukan ini. Mau bagaimana lagi?”.
“Kita lakukan saja politik uang. Masyarakat kan juga butuh uang. Bagikan saja kepada mereka. Nanti kita arahkan supaya memilihmu”.“Tidak usah. Aku tidak mau menggunakan cara curang untuk memproleh simpati. Biarlah air mengalir dengan caranya sendiri. Kita ikuti saja alurnya”.
Hari pemilihan tiba. Warga antusias menentukan pilihannya masing-masing. Aku tidak mengintervensi mereka. Biarlah mereka memilih pemimpinnya dengan perhitungannya sendiri.
Tanpa ada paksaan. Mereka mengerti apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan pemimpin yang memahami kondisi mereka. Yang peduli akan kehidupan dan nasib mereka.
Tidak membutuhkan janji palsu yang diumbar selama kampanye. Yang mereka butuhkan adalah realisasi dari janji para calon pemimpinnya. Aku kalah dari sang petahana. Bahkan suaraku kalah jauh. Aku tidak dapat menyembunyikan kekecewaanku. Aku harus menerima konsekuensi politik.
Partai pengusung berhamburan mendukung petahana. Mereka tidak mempedulikan aku yang sudah kalah. Setidaknya mereka beranggapan kalau karirku di dunia politik sudah berakhir.
Padahal ini hanya awal dari perjalanan politikku. Aku harus bangkit. Yang kuperlukan saat ini hanya motivator yang mampu membangkitkanku dari keterpurukan dan selalu berkata:
“Jangan menyerah. Ini hanya awal dari perjalanan hidup. Teruslah mencoba untuk memproleh pengalaman hidup yang lebih baik”. Itulah bapak dan istriku.
Cerpen Karangan: Angga Eko Ardianto
Blog / Facebook: Angga Eko Ardianto
Identitas Penulis
TTL: Probolinggo, 18 Maret 1996
Alamat: Jalan Panglima Sudirman GG. Treman no. 64
Kota Probolinggo
Email: anggaekoardianto07@yahoo.com